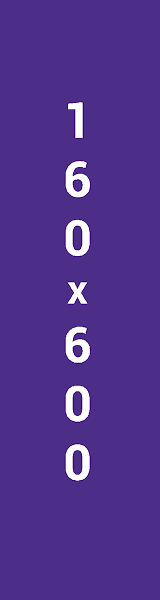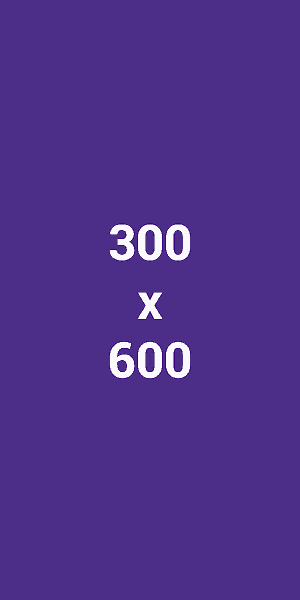POLITIKAL.ID - Tewasnya jenderal penting di tubuh satuan elite Garda Revolusi Iran, Qassem Soleimani, telah memanaskan suhu politik global. Ancaman perang di kawasan Timur Tengah disebut-sebut sebagai ongkos mahal yang mesti diterima rezim Trump.
Pembunuhan Soleimani didasari anggapan bahwa sang jenderal terlibat dalam serangkaian aksi terorisme yang, menurut Trump, sudah menewaskan banyak warga AS. Menghabisi Soleimani, pendek kata, adalah langkah (realistis) agar teror berhenti.
Namun, di saat bersamaan, kebijakan Trump membunuh Soleimani juga dapat dibaca sebagai upaya untuk meningkatkan elektabilitas menjelang Pilpres 2020, November mendatang. Ia ingin publik memberikan simpati dan dukungan di tengah citranya yang kadung ambyar dengan sederet skandal yang berujung pada pemakzulan (impeachment).
Dunia politik AS menyebutnya rally ‘round the flag effect.
View this post on Instagram
Bagaimana Munculnya? Konsep rally ‘round the flag effect pertama kali muncul dalam balada “Battle Cry of Freedom” karya George Fredrick Root pada 1862, atau saat Perang Sipil Amerika meletus.
Lambat laun, ungkapan itu dipakai dalam studi politik dan hubungan internasional untuk memperlihatkan relasi antar popularitas presiden AS dan peristiwa internasional tertentu. Richard Neustadt dan Kenneth Waltz merupakan dua ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan konsep tersebut ke publik.
Adalah John Mueller yang kemudian menggali lebih jauh konsep rally ‘round the flag effect. Pemikirannya dituangkan ke dalam buku berjudul War, Presidents, and Public Opinion yang dirilis pada 1973.
Lewat bukunya, Mueller menerangkan bahwa rally ‘round the flag effect merupakan bagian dari variabel independen penentu popularitas presiden. Dalam definisi Mueller, rally ‘round the flag effect memuat tiga kriteria: peristiwa yang bersifat global, melibatkan AS dan presiden secara langsung, serta berefek dramatis.
Penelitian Mueller memperlihatkan peristiwa internasional tertentu, yang melibatkan partisipasi pemerintah AS, biasanya berbanding lurus dengan melonjaknya popularitas presiden. Alasannya, Mueller bilang, masyarakat AS tak ingin menyaksikan negaranya gagal di tingkat internasional. Selain itu, peristiwa internasional juga dapat menjadi medium bagi presiden untuk mempertontonkan patriotismenya kepada khalayak.
Tapi, aksi presiden bukan faktor tunggal yang menentukan keberhasilan rally ‘round the flag effect. Dalam “The Rally ‘Round the Flag Effect: A Look at Former President George W. Bush and Current President Barack Obama” (PDF, 2013), Jocelyn Norman menerangkan bahwa persepsi publik turut pula dipengaruhi oleh media, elite, dan retorika politik.
Media, misalnya, berperan membingkai pemberitaan sekaligus menyebarluaskan informasi terkini mengenai respons pemerintah di tengah krisis internasional. Tak lama usai serangan 11 September yang menghancurkan World Trade Center, publik AS berada pada kondisi yang terancam dan media massa memainkan perannya: membingkai terorisme dengan cara sensasional sehingga meningkatkan kemungkinan persetujuan masyarakat terhadap kebijakan luar negeri pemerintah—yang sebetulnya belum tentu semuanya sepakat.
Awal-awal masa krisis, tulis Jocelyn, liputan media biasanya “tidak berdarah-darah dan patriotik” sehingga membantu pembentukan konsensus di antara para elite. Tak hanya itu saja, di waktu yang sama, pers juga memberikan porsi cukup banyak kepada kelompok pro-perang. Suara yang kritis menolak perang serta oposisi seringkali diabaikan. Dengan demikian, informasi dari media mempunyai efek besar bagi publik karena mereka punya siasat tersendiri dalam menyajikan krisis internasional.
Sementara elite dan retorika politik juga menjadi faktor penting dalam kesuksesan rally ‘round the flag effect. Bila dikemas secara sederhana dan menarik, pidato presiden ketika menanggapi krisis internasional bakal mendulang banyak dukungan dari masyarakat. Karena, terlepas dari kebijakan yang diambil, krisis bisa membuat publik bersatu dan membeli apa saja yang keluar dan dijual Gedung Putih. Contohnya, reaksi publik pasca-serangan 11 September 2001.
Sejarah mencatat bahwa rally ‘round the flag effect bukan sebatas pepesan politik yang kosong. Presiden AS sudah banyak yang menikmati keuntungan dari peristiwa internasional tertentu.
Barack Obama, misalnya, mendapatkan kenaikan sembilan poin—menjadi 56 persen—usai Osama bin Laden dihabisi tentara AS di Pakistan pada 2011. Kenaikan poin Obama, rupanya, bukanlah rekor dalam jagat politik AS.
Popularitas John F. Kennedy naik 12 poin setelah Krisis Rudal Kuba. Presiden Ford mendapatkan lonjakan 11 poin usai militer AS berusaha menyelamatkan kapal dagang Mayaguez. George H.W. Bush memperoleh 24 poin ketika Operasi Badai Gurun dilakukan.
Kemudian popularitas Franklin Roosevelt naik 12 poin pasca-serangan Pearl Harbor. Jimmy Carter meroket 13 poin setelah demonstran Iran mengepung Kedubes AS di Teheran. Sedangkan Nixon mendapatkan 16 poin tak lama usai meneken perjanjian damai yang mengakhiri Perang Vietnam. Namun demikian, rekor tetap dipegang George W. Bush. Ia memperoleh 35 poin usai serangan 11 September.
Menurut catatan Council on Foreign Relations, pola dari rally ‘round the flag effect dapat digambarkan seperti berikut: masyarakat AS cenderung lebih mendukung presiden usai peristiwa besar, terlepas apakah itu berakhir baik atau buruk.
Statistik yang dihimpun Gallup memperlihatkan bahwa rata-rata presiden AS memperoleh kenaikan tujuh poin dengan rally ‘round the flag effect. Kenaikan tersebut hanya bertahan sekitar, maksimal, empat minggu.
William Baker dan John Oneal dalam penelitian berjudul “Patriotism or Opinion Leadership?: The Nature and Origins of the “Rally ‘Round the Flag” Effect” (2001) yang terbit di The Journal of Conflict Resolution menerangkan rally ‘round the flag effect akan efektif bekerja—dan menghasilkan keuntungan poin—pada kondisi: ketika AS melawan kekuatan besar sampai ada tujuan revisionis (mendorong Irak angkat kaki dari Kuwait, misalnya).
Anomali Trump
Hampir setiap presiden AS mendapatkan kenaikan poin usai peristiwa internasional. Namun, itu tak berlaku buat Trump.
Padahal, rezim Trump bisa dibilang tak sepi peristiwa internasional. Dalam hanya rentang kurang dari setahun (hingga awal Januari 2020), Trump sudah menghabisi dua sosok penting: Baghdadi serta Soleimani. Yang satu panglima ISIS, lainnya jenderal Garda Revolusi.
Dua peristiwa itu berpotensi mengerek popularitas Trump. Kenyataannya, tingkat popularitas Trump tak terdampak secara signifikan.
Data dari FiveThirtyEight memperlihatkan, sejak Maret 2017, tingkat ketidaksukaan masyarakat terhadap Trump selalu berada di kisaran angka 50 persen. Data terbaru yang dilansir 2 Januari 2020 menunjukkan persentase ketidaksukaan tersebut bahkan menyentuh angka 53,1 persen. Hasil serupa juga muncul dalam jajak pendapat Gallup: approval rating Trump hanya berada di angka 45 persen (Desember 2019).
Peter Nicholas dalam “Trump Cultivated His Own Credibility Crisis on Iran” yang dipublikasikan The Atlantic (2020) menulis bahwa alasan mengapa popularitas Trump tak berubah adalah karena kredibilitasnya di mata masyarakat AS telah lebih dulu remuk.
Selama Trump menjabat, publik melihat betapa bebal dan sembrononya ia mengambil kebijakan. Trump menjadikan pemerintahannya one man show yang bikin publik muak. Ia seenaknya memecat pejabat, menuduh media-media arus utama menyebarkan hoaks, dan lebih suka berkelahi di Twitter ketimbang merumuskan program yang komprehensif.
Tak hanya itu, Trump juga terlibat banyak dugaan skandal: dari keterlibatan Rusia dalam Pilpres 2016 yang mengantarkannya naik ke tampuk kekuasaan sampai ancaman pemotongan bantuan militer bagi Ukraina sehubungan kasus Biden. Yang disebut terakhir bahkan berujung pemakzulan dirinya oleh Partai Demokrat.
Alih-alih mendapatkan lonjakan popularitas, reputasi Trump diprediksi malah kian jatuh. Pasalnya, keputusannya untuk menghabisi nyawa Soleimani bisa jadi melahirkan aksi balasan yang tak kalah mengerikan—mengancam nyawa warga AS, khususnya di Timur Tengah. Terlebih, para pengkritik juga berpandangan keputusan tersebut diambil guna memenuhi ambisi Trump—daripada demi kepentingan nasional.
"Satu lagi: Trump menghabisi Soleimani tanpa lebih dulu berkonsultasi dengan Kongres. Keputusan itu diambil sewaktu ia tengah liburan di Florida."
Rasanya wajar bila popularitas Trump tak berubah signifikan. (*)
Artikel ini telah tayang di Tirto.id dengan judul Cara Trump Olah Isu Terorisme demi Elektabilitas